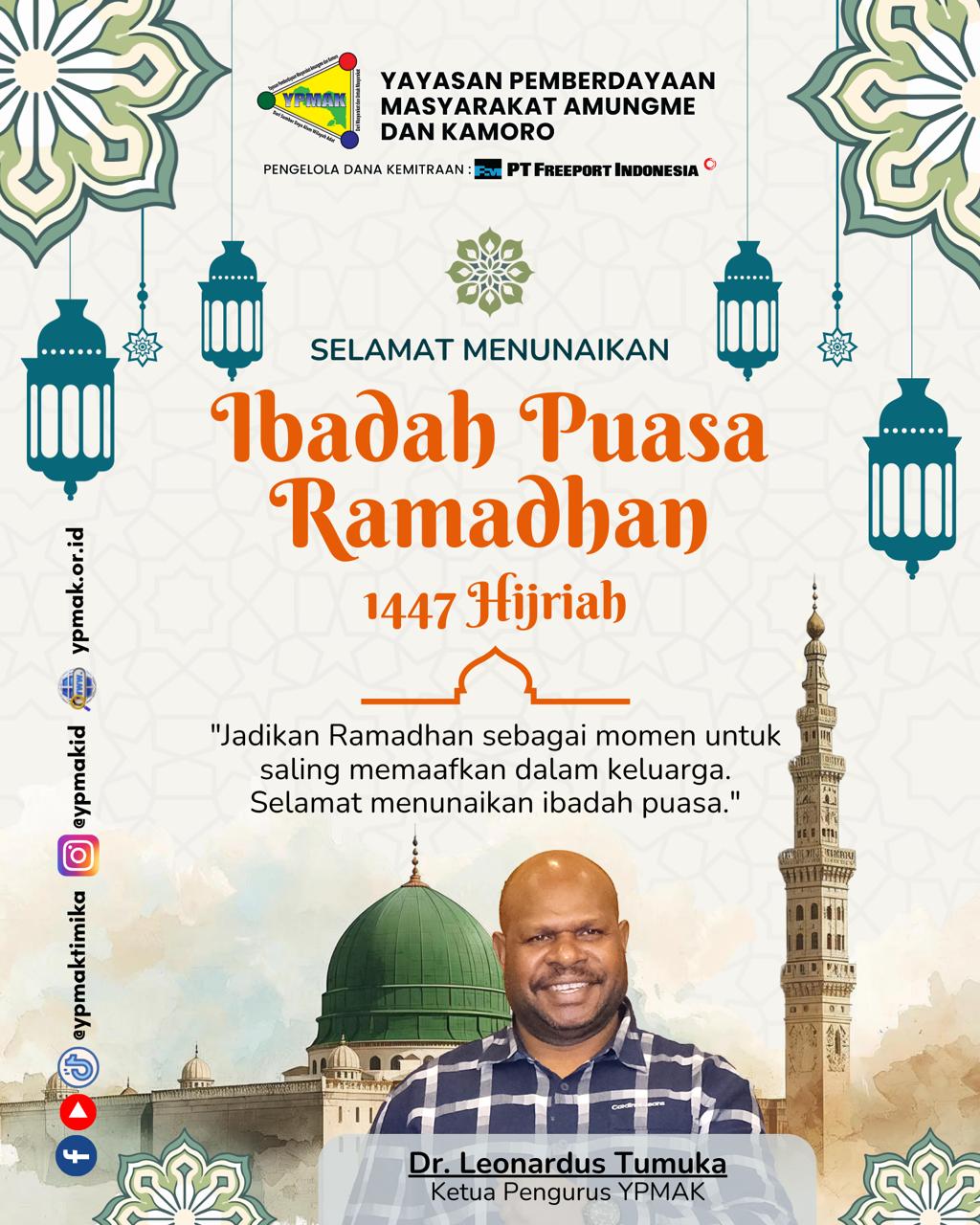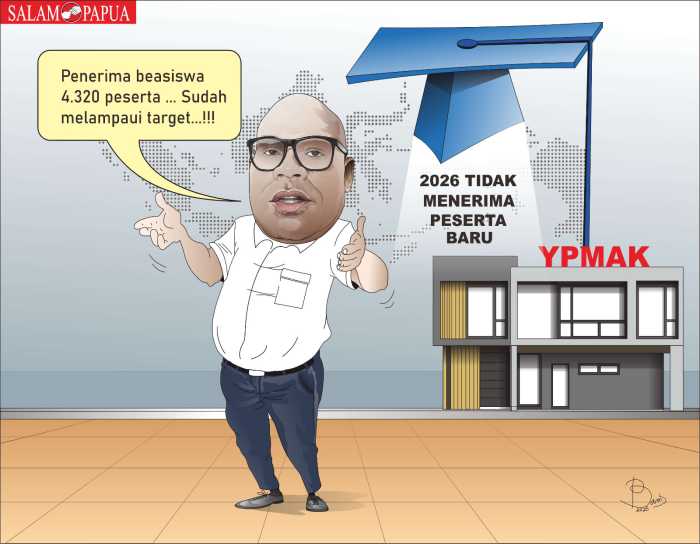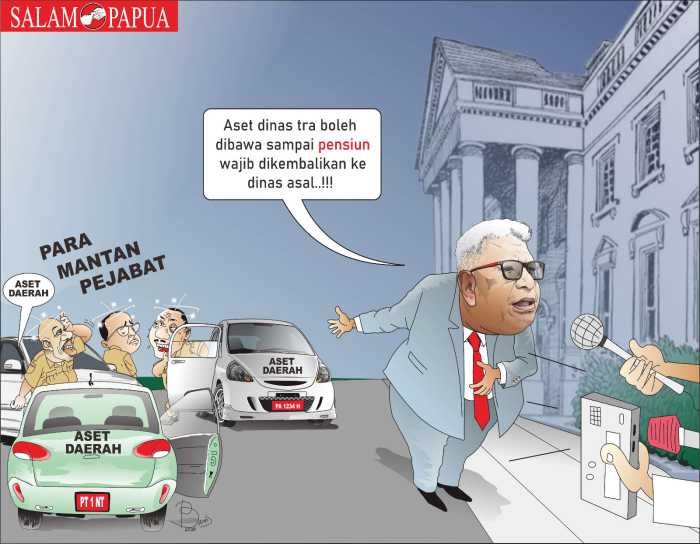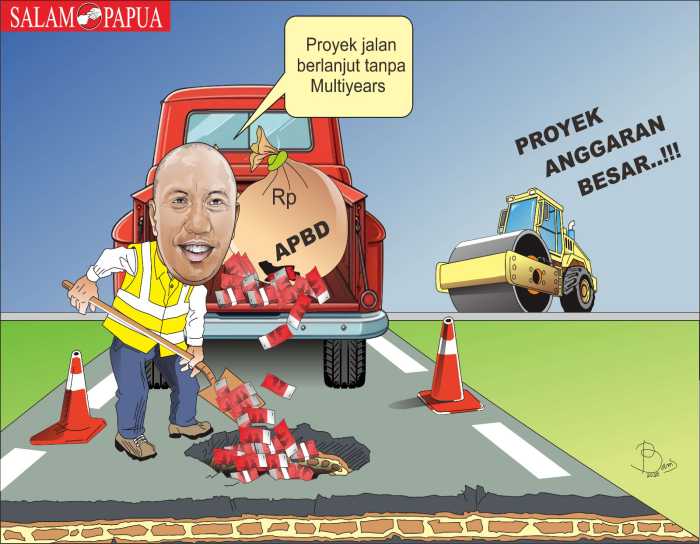SALAM PAPUA (TIMIKA)- Penolakan terhadap perkebunan kelapa
sawit di Tanah Papua bukanlah sikap anti-pembangunan, sebagaimana sering
dituduhkan. Penolakan ini lahir dari kesadaran kolektif masyarakat adat bahwa
tanah, hutan, dan seluruh kehidupan di dalamnya bukan sekadar ruang ekonomi,
melainkan fondasi keberlangsungan hidup orang Papua dan makhluk lain yang hidup
berdampingan di dalamnya.
Bagi masyarakat adat Papua, tanah adat bukan aset yang bisa
diganti dengan uang atau janji kesejahteraan jangka pendek. Tanah adalah
identitas, ruang spiritual, sumber pangan, obat-obatan tradisional, serta
tempat berlangsungnya relasi sosial lintas generasi. Ketika tanah adat
dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit skala besar, yang hilang bukan hanya
hektare hutan, tetapi juga sistem kehidupan yang telah dijaga turun-temurun.
Ekspansi sawit di Papua kerap berjalan di atas model
pembangunan ekstraktif yang mengabaikan persetujuan bebas, didahului, dan
diinformasikan secara utuh (Free, Prior and Informed Consent/FPIC). Dalam
banyak kasus, masyarakat adat tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses
pengambilan keputusan, sementara izin konsesi diberikan di atas wilayah ulayat
mereka. Negara hadir lebih sebagai pemberi karpet merah bagi investasi
ketimbang pelindung hak konstitusional rakyat.
Dampak ekologis dari perkebunan sawit juga tidak bisa
diabaikan. Papua merupakan salah satu benteng terakhir hutan hujan tropis
Indonesia yang menjadi habitat berbagai satwa endemik, seperti cenderawasih,
kasuari, kanguru pohon, hingga beragam spesies reptil dan serangga yang belum
seluruhnya teridentifikasi secara ilmiah. Pembukaan hutan untuk sawit berarti
menghancurkan habitat satwa, memutus koridor ekologis, dan mendorong kepunahan
perlahan yang sering kali tak tercatat.
Konflik antara manusia dan satwa liar juga meningkat seiring
menyempitnya ruang hidup. Satwa yang kehilangan habitat terpaksa masuk ke
wilayah permukiman atau kebun masyarakat, lalu dianggap sebagai hama dan
diburu. Dalam situasi ini, satwa menjadi korban ganda: kehilangan rumah dan
kehilangan nyawa.
Ironisnya, semua kerusakan ini kerap dibungkus dengan narasi
pembangunan dan kesejahteraan. Padahal, pengalaman di berbagai wilayah
menunjukkan bahwa sawit tidak otomatis meningkatkan kualitas hidup masyarakat
adat. Yang tersisa justru ketergantungan ekonomi, konflik internal, serta
kerusakan lingkungan yang bersifat permanen.
Penolakan sawit di Papua sesungguhnya adalah seruan untuk
mengubah arah kebijakan pembangunan. Negara seharusnya menempatkan perlindungan
tanah adat sebagai fondasi utama, bukan hambatan pembangunan. Pengakuan dan
perlindungan wilayah adat, penguatan pangan lokal, serta ekonomi berbasis hutan
lestari merupakan jalan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Melindungi tanah adat Papua berarti juga melindungi satwa,
hutan, dan masa depan generasi mendatang. Jika hutan Papua hilang, bukan hanya
orang Papua yang kehilangan, tetapi dunia kehilangan salah satu penyangga
kehidupan terakhirnya. Di titik inilah penolakan sawit menjadi bukan sekadar
isu lokal, melainkan persoalan moral dan tanggung jawab bersama.
Masyarakat adat di Tanah Papua diminta untuk memperkuat
persatuan internal dan mempertegas hak atas tanah ulayat dalam menyikapi
masuknya investasi perkebunan kelapa sawit di berbagai wilayah Papua.
Sejumlah pemerhati masyarakat adat dan lingkungan menilai,
ekspansi sawit kerap memicu konflik sosial, perpecahan internal, serta
hilangnya ruang hidup masyarakat adat jika tidak disikapi secara kolektif dan
berbasis hukum.
Selain itu, masyarakat adat juga didorong untuk memperjelas
status wilayah adat melalui pemetaan partisipatif dan penguatan lembaga adat.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penerbitan izin usaha di atas tanah
ulayat tanpa sepengetahuan pemilik hak adat.
Masyarakat adat juga disarankan membangun jejaring dengan
lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, serta pendamping hukum guna
memperkuat posisi tawar di hadapan pemerintah dan investor. Dukungan lintas
pihak dinilai penting untuk mencegah kriminalisasi warga yang menolak sawit.
Di sisi lain, pemerintah didorong untuk membuka ruang dialog
yang adil dan transparan dengan masyarakat adat sebelum menerbitkan izin
perkebunan sawit. Pemerintah juga diminta mengedepankan model pembangunan
alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berbasis potensi lokal, seperti
pangan lokal dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Penolakan terhadap sawit di Papua selama ini juga berkaitan
dengan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap satwa
endemik Papua. Pembukaan hutan untuk perkebunan sawit dinilai berpotensi
menghilangkan habitat satwa liar serta memperparah konflik manusia dan satwa.
Untuk menyikapi hal ini, Pemerintah pusat dan daerah diminta
mengambil langkah konkret dan terukur dalam menyikapi penolakan masyarakat adat
terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit di Tanah Papua. Penolakan tersebut
dinilai sebagai sinyal kuat adanya persoalan mendasar dalam tata kelola
perizinan, perlindungan hak ulayat, dan keberlanjutan lingkungan.
Sejumlah pemerhati kebijakan publik dan hak masyarakat adat
menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin
perkebunan sawit yang telah diterbitkan, terutama yang berada di atas wilayah
adat dan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi.
Pemerintah juga diminta membuka ruang dialog yang setara dan
transparan dengan masyarakat adat sebelum mengambil keputusan terkait investasi
sawit. Dialog tersebut harus melibatkan lembaga adat, tokoh agama, perempuan,
dan generasi muda, serta memastikan penerapan prinsip FPIC.
Selain dialog, pemerintah didorong mempercepat pengakuan dan
perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan wilayah ulayatnya. Pengesahan
peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat adat dinilai menjadi langkah
strategis untuk mencegah konflik agraria dan tumpang tindih perizinan.
Di sektor lingkungan, pemerintah diminta memperketat
pengawasan terhadap perusahaan perkebunan sawit, termasuk pelaksanaan AMDAL,
perlindungan habitat satwa liar, serta kepatuhan terhadap ketentuan kehutanan
dan lingkungan hidup. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dinilai penting
untuk memulihkan kepercayaan publik.
Pemerintah juga didorong mengembangkan model pembangunan
alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berbasis potensi lokal Papua,
seperti penguatan pangan lokal, ekonomi hutan lestari, dan usaha masyarakat
adat, sebagai pilihan selain perkebunan sawit skala besar.
Penulis: Sianturi