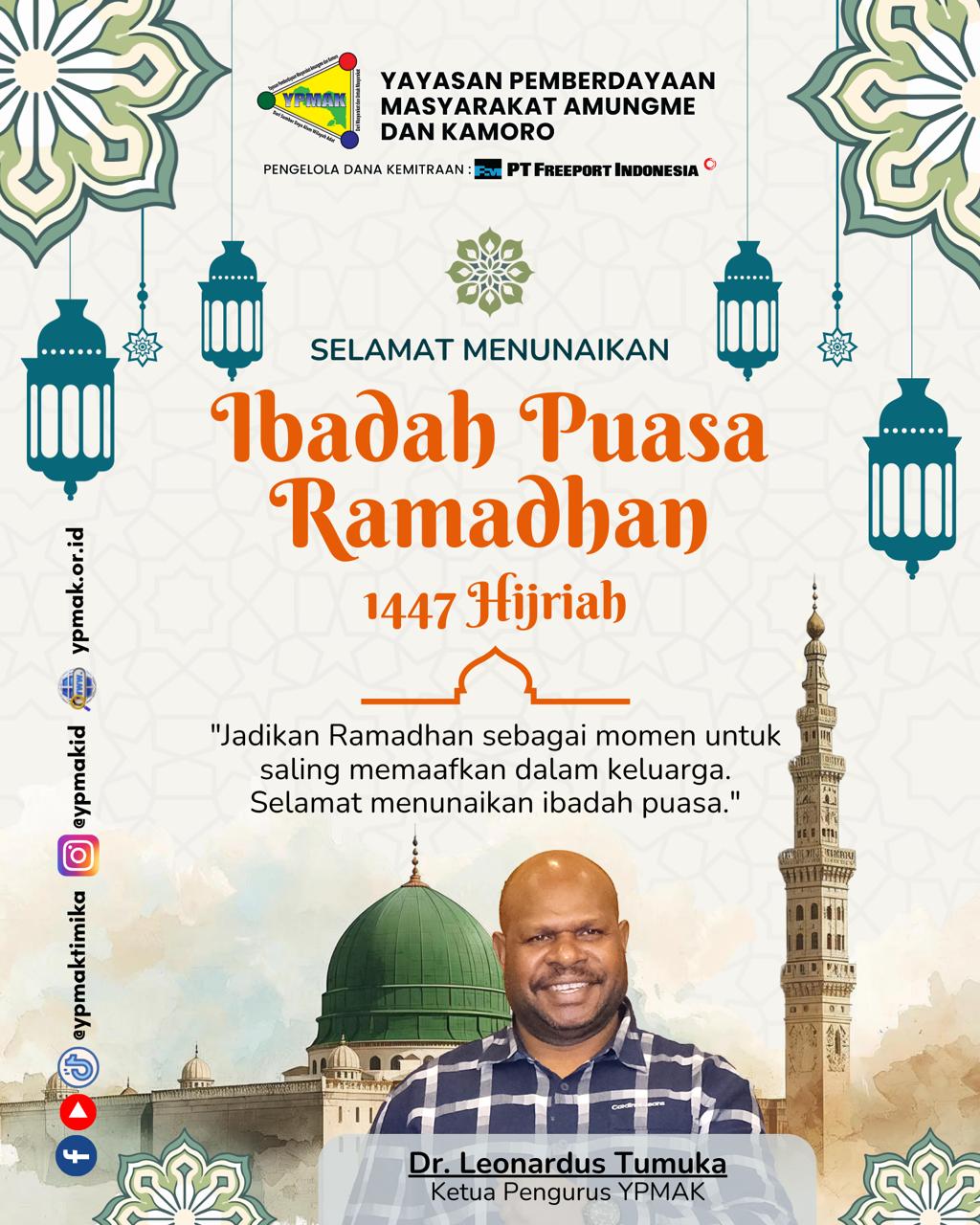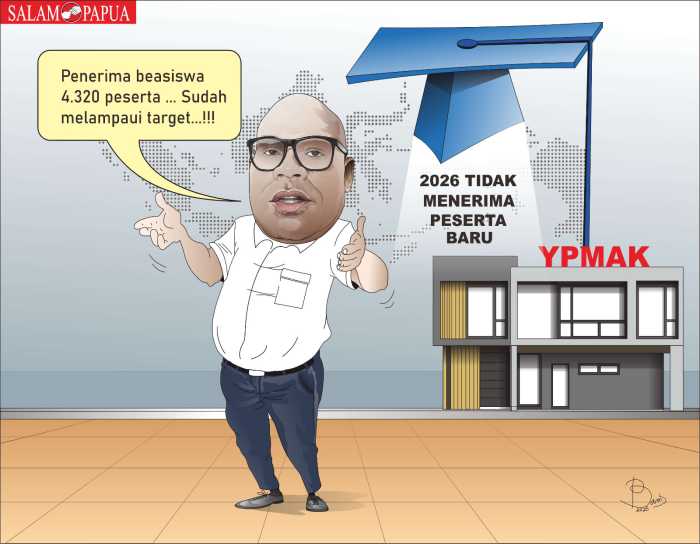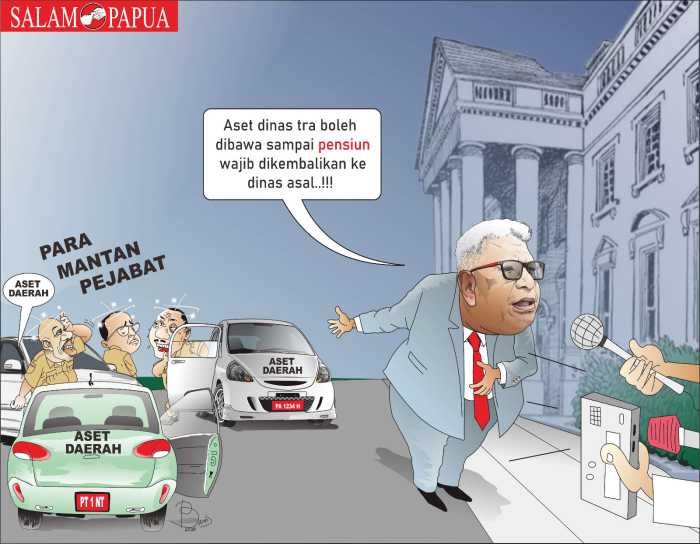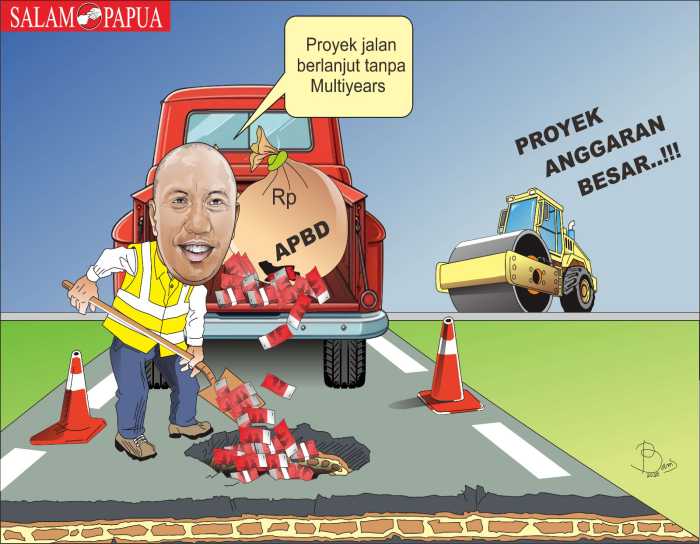SALAM PAPUA (TIMIKA)- Pada 14 Mei 2024, di Auditorium
Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua, dilangsungkan acara bedah buku
berjudul “Mengurai Benang Kusut Keadilan Perkara Barnabas Suebu”. Buku sebanya 263 halaman yang ditulis oleh
Dr. Stefanus Laksanto Utomo, S.H., M.Hum., itu menghadirkan beberapa ahli dalam
bidang hukum secara hybrid, yakni luring (offline) dan daring (online), antara
lain, Prof. Gayus Lumbuun via teleconference, Prof. Robert K.R. Hammar, dan Dr.
Basir Rohrohmana, serta keynote speaker Marzuki Darusman, S.H (teleconference)
ini mengurai berbagai isu pokok dalam eksaminasi perkara Barnabas Suebu dalam
sistem peradilan Indonesia yang tidak berjalan
efektif, terlanggarnya hak azasi manusia, serta putusan hakim yang
kurang objektif karena tidak menunjukkan independesinya.
Barnabas Suebu atau akrab disapa “Kaka Bas” didakwa oleh
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan
dakwaan alternatif, yaitu penyalahguaan wewenangnya sebagai Gubernur Papua
kurun 2006-2011, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999
tentang Perbuatan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dan dikorelasikan dengan Pasal
55 dan 56 KUHP perihal turut melakukan dan membantu melakukan suatu tindak
pidana kejahatan (korupsi). Dakwaan yang sama juga disematkan kepada Direktur
Utama (Dirut) PT. Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ) La Musi Didi, dan
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua) Jannes Johan Karubaba. Bas
atau Terdakwa dituduh menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri
sendiri, orang lain, atau korporasi, dan kerugian negara dengan mempengaruhi
dalam proses pengadaan kegiatan pembuatan proyek perencanaan fisik atau lazin
disebut Detail Engineering Design (DED) yang meminta agar PT KPIJ yang
merupakan perusahaan milik Terdakwa (Bas) atau keluarganya untuk diikutsertakan
dalam pelaksanaan pembuatan DED bersama dengan perusahaan yang telah ditetapkan
sebagai pemenang lelang dalam proyek pembuatan DED Sentani dan Paniai tahun
anggaran 2008, DED Urumka I, II, dan III, serta DED Pembangkit LIstrik Tenaga
Air (PLTA) Mamberamo I dan II untuk tahun anggaran 2008-2010.
Atas permintaan tersebut, La Musi Didi dengan menggandeng
PT. Indra Karya Cabang Malang dan PT Geo Ace, dengan kesepakatan pembagian
keuntungan dan pemberian fee pada pihak-pihak terkait, yakni 60 persen PT Indra
Karya dan 40 persen PT KPIJ. Proses lelang proyek pembuatan DED Sentani dan
Paniai, DED Sungai Urumka I, III, dan III, seolah-olah berjalan sesuai prosedur
pelelangan, dengan seluruh dokumen administrasi lelang dan kontrak digarap oleh
PT Indra Karya, tetapi kenyataannya panitia pengadaan tidak melaksanakan lelang
proyek DED Urumka I. Dari semua proses lelang dan pelaksanaan DED dilaporkan
oleh La Musi kepada Terdakwa yang berkapasitas sebagai Gubernur Papua.
Bahkan dinilai lelang tersebut dilaksankan tanpa
memperhatikan Pasal 5 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, yang
menyebutkan, “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang
terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, yaitu
antara lain: huruf e: menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses
pengadaan barang/jasa (conflic of interest). Huruf g: menghindari dan mencegah
penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk menguntungkan
pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan negara (St. Laksanto Utomo: 2024).
Rangkaian proses tersebut, Bas didakwa melakukan korupsi,
dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan (memperkaya) diri
sendiri, orang lain, atau korporasi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp
43 miliar.
Dari kasus ini, Bas divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada November 2015,
dengan amar putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor
67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST, yang menyatakan, Terdakwa Barnabas Suebu telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kedua”. Hakim menjatuhkan putusan
terhadap Terdakwa tanpa menguraikan bukti kesalahannya. Hakim secara subjektif
menyimpulkan bahwa Terdakwa terlah melakukan perbuatan melawan hukum dan
memenuhi unsur tindak pidana yang dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31
Tahun 1999 tentang PTPK, yakni menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri
sendiri, orang atau korporasi, dikaitkan dengan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang turut serta dan membantu melakukan,
yang memiliki makna bahwa orang yang mengetahui dan dimintai bantuan untuk
memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan itu tanpa mencegah.
Sayangnya, hakim Tipikor hanya melihat unsur-unsur pidana
secara umum, yang meliputi unsur secara melawan hukum, melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta dapat merugikan
negara atau perekonomian negara, tanpa mengelaborasi secara rinci terkait
posisi atau peran Terdakwa (Bas) dalam melakukan tindak pidana korupsi, dengan
disertakan dasar-dasar hukumnya. Seharusnya hakim dalam pertimbangan hukumnya
mengurai secara benderang kasus ini, dengan menampilkan bukti-bukti yang relevan
dan dapat bersesuaian satu dengan lainnya, agar bisa ditarik benang merah dan
diketahui kausalitasnya, hingga bisa ditententukan posisi atau letak kesalahan
Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Menurut doktrin hukum pidana,
untuk menjatuhkan hukuman seseorang haruslah memenuhi kedua unsur tindak
pidana, yaitu unsur kesalahan dan unsur perbuatan melawan hukum (St. Laksanto
Utomo: 2024). Namun, tampak hakim Tipikor Jakarta Pusat belum membuktikan unsur
kesalahan yang melekat pada Terdakwa, maka putusan hakim terhadap Terdakwa yang
menimbulkan polemik hingga sekarang dinilai dipengaruhi pertimbangan di luar
hukum (non-yuridis).
Sebab, unsur-unsur pidana dalam setiap pasal memiliki makna
yang berbeda-beda, karena itu penjelasan secara gamblang terhadap setiap pasal
yang didakwakan terhadap Terdakwa sangatlah diperlukan. Misalnya, perbedaan
antara Pasal 2 dan 3 UU PTPK, yang mana Pasal 3 menyebutkan, pelaku bisa
dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan di Pasal 2, menyatakan, setiap
orang yang dimaksud dalam pasal tersebut lebih luas dan umum. Unsur setiap
orang adalah yang punya kewenangan. Jadi perbuatan seseorang bisa saja bersifat
melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Sebab dalam hukum
pidana sebuah pembuktianan harus objektif dan akurat, sebagimana dikenal dalam
postulat in criminalibus probationes bedent esse luce clariores (dalam
perkara-perkara pidana bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya). Dan
tidak dibenarkan dalam teori apa pun bahwa menegakkan hukum dengan cara melawan
hukum, kecuali demi menegakkan hak azasi manusia (atau demi intervensi
kemanusiaan).
Selanjutnya, tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, Terdakwa (Bas) melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan
Tinggi (PT) Jakarta untuk meminta keringanan hukuman. Di tingkat banding, PT
Jakarta memperberat hukuman Terdakwa menjadi 8 tahun penjara (2016) dan pada
tingkat kasasi di Mahkamah Agung juga memperkuat putusan PT Jakarta bahwa
Terdakwa tetap dipenjara 8 tahun. Bahkan upaya hukum luar biasa atau peninjauan
kembali (PK) Bas pun ditolak. Padahal, sesuai fakta-fakta yang terungkap di
persidangan sangat kontras dan berbeda jauh dari semua dalil-dalil yang
dituduhkan penuntut umum dalam surat dakwaan, yakni tidak dibuktikan di mana
letak kesalahan atau peran Terdakwa (Bas) dalam kasus a quo. Terdakwa sendiri
telah membantah atas dakwaan yang disusun oleh penuntut umum yang menurutnya bersifat
imajinasi atas kesaksian palsu yang diberikan oleh para saksi yang dihadirkan
dalam penyidikan. “Kesaksian palsu itu bersifat fintah atas diri saya (Terdakwa
Bas Suebu) dan mencemarkan nama baik serta kehormatan saya,“kata Terdakwa saat
menanggapi surat dakwaan Jaksa pada KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta
(detiknews: 2015).
Tidak ada fakta yang mengungkap bahwa Terdakwa melakukan
perbuatan melawan hukum, yaitu menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan,
turut serta (deelneming), membantu, atau berbarengan (samenloop, concursus) melakukan
rasuah, dengan memperkaya diri, orang lain, atau korporasi. Karena perbuatan
melawan hukum (unlawful act) merupakan unsur paling pokok dalam tindak pidana
yang mencakup adanya kesalahan, yang
terjadi karena kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpue), sebagaimana
dirumuskan oleh ahli hukum Jerman, Paul Johann Anselm Ritter Von Feuerbach
(1775-1833) sebagai peletak dasar asas legalitas yang dikenal dalam maksim
nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tiada suatu perbuatan
dapat dipidana kecuali ada aturan pidana atau peraturan perundangan-undangan
yang telah mengaturnya).
Asas tersebut telah dinormakan dalam hukum positif (ius
scripta) sebagai bentuk azas legalitas
yang dianuat Indonesia, yakni Pasal 1
ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana,
kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Juga diingat
kembali filosofi keadilan ubi jus incertum, ibi jus nullum (di mana tidak ada
kepastian hukum, di situ tidak ada hukum). Bahkan dalam kasus pidana berlaku
juga azas nulla poena sine culpa atau geen straf zonder schuld, yang artinya
tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam kasus ini tidak dimunculkan adanya unsur
actus reus (perbuatan) dan mens rea (niat) dari Terdakwa dalam melakukan tindak
pidana korupsi.
Hal ini berangkat dari surat dakwaan penuntut umum maupun
vonis hakim terhadap Terdakwa yang tidak memiliki bukti yang kuat dan
meyakinkan, sebagaimana terungkap dalam persidangan. Padahal, dakwaan adalah
mahkota persidangan dan pembuktian (berwijsvoering) merupakan jantung dari
persidangan,yang diabaikan oleh penuntut umum dan hakim dalam mendakwa, menuntut,
dan memutus perkara korupsi Bas. Jaksa selaku pemilik dominus litis (pengendali
perkara) tidak mampu menunjukkan bukti permulaan yang cukup sebagai syarat
formil sekaligus menjadi pintu masuk untuk dijadikan Bas sebagai tersangka
kasus korupsi, seturut asas actori incumbit onus probandi (siapa yang
mendakwa/menuntut, dialah yang wajib membuktikannya) atau dalam perpektif hukum
perdata dikenal asas affirmati incumbit probate (siapa mendalilkan sesuatu,
wajib membuktikannya). Surat dakwaan menjadi unsur terpenting karena memuat
unsur locus delicti (tempat terjadinya tindak pidana), tempus delicti (waktu
terjadinya tindak pidana), dan corpus delicti (alat atau barang bukti dari
suatu tindak pidana), sekaligus menentukan intellectual dader (pelaku) atau medepleger
(orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu
perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam
melaksanakan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati).
Bahkan, setiap putusan hakim mengacu pada dakwaan dan bukti
yang terungkap dalam persidangan, termasuk kayakinan hakim sebagaimana bunyi
asas judex debet judicare secundum allegate et probate, yang berarti hakim
harus memberikan keputusan berdasarkan dakwaan dan bukti-buktinya. Selanjutnya
dalam Pasal 183 KUHAP secara expressive verbis menyatakan, “Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Maka,
terdakwalah yang berkewajiban mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, yang
selaras dengan adagium culpue poena par esto/let the punishment be equal the
crime (jatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya) atau ut sementem
faceris ita metes (siapa yang menanam sesuatu dialah yang memetik hasilnya).
Tidak mungkin menegakkan hukum materil tanpa terpenuhinya
syarat formil. Pendek kata, hukum formil menjadi syarat tegaknya hukum materil.
Jika tidak ada dua alat bukti permulaan yang cukup sebagai syarat formil dalam
proses hukum pidana, secara otomatis hukum materil tidak terlaksana. sejumlah
alat bukti yang dihadirkan jaksa di persidangan, baik saksi mahkota atau saksi
memberatkan (saksi fakta) dan alat bukti lain yang harus relevan dan saling
bersesuaian. Meski banyak saksi yang dihadirkan oleh jaksa, tetapi
keterangannya tidak berkualitas: tidak menjelasan secara detail apa peran, di
mana, kapan terjadinya praduga tindak pidana korupsi? Keterangan saksi juga
harus didukung oleh alat bukti lain yang cukup valid dan sahih, dengan kualitas
pembuktiannya yang tak terbantahkan (tidak adak keraguan sama sekali), di
situlah calon tersangka bisa dapat diduga kuat telah melakukan suatu tindak
pidana korupsi dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Tanpa dukungan
alat bukti permulaan lain yang cukup dan tidak bersesuaian dengan keterangan
saksi, maka tidak ada gunanya keterangan saksi, hingga Terdakwa harus
dihentikan dari kasusnyadi tingkat penyelidikan dan penyidikan, baik itu
melalui proses praperadilan atau dikeluarkan surat perintah penghentian
penyidikan (SP3).
Juga atas kekuasaan dan kewenangan yang amat vital dan
strategis yang dimiliki jaksa dalam menjaga keadilan dan merawat keberlanjutan
hukum dalam sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga
pelaksanaan putusan pengadilan, yang diakui selaku pemilik dominus litis
(pengendali perkara), bisa melaksanakan kebijakan hukum berupa keadilan
restoratif (restorative justice). Hal tersebut sesuai dengan Paraturan
Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif . Artinya,
mekanisme penyelesaikan perkara tidak mengedepankan pemidanaan, melihkan
keadaan korban atau pemulihan pada kondisi semula (restitutio ad/in integrum).
Jelas sekali jaksa tidak menguasai anatomi perkara, hingga konstruksi kasus
dalam surat dakwaan pun semrawut, sumir, dan jauh dari fakta yang sebenarnya.
Padahal jaksa dituntut untuk memiliki kapabilitas yang mempuni, integritas, dan
profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Jaksa harus mempunyai kemampuan
teknis maupun yuridis, sehingga dalam penanganan perkara, jaksa senantiasa
menguasi anatomi perkara, memahami normatif yuridis, mencermati aspek sosial
terdakwa (pelaku), korban, dan masyarakat. Serta mempertimbangkan syarat
subjektif tentang perlu atau tidaknya melakukan penahan, tanpa harus berkutat
dan terkungkung dengan prinsip legalitas formal yang tidak perlu dan melahirkan
diorientasi penegakan hukum yang jauh dari aspek keadilan (Bambang Soesatyo:
2024).
Maka, tidak dapat dibenarkan jaksa maupun hakim menyatakan
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakuan perbuatan melawan hukum,
yakni korupsi dengan unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” diri sendiri, orang
lain, atau korporasi. Jaksa dan hakim harus berani berkata jujur dan
membuktikan letak kesalahan Terdakwa yang bisa dibenarkan secara hukum serta
diakui nalar publik, karena pengakuan itu datang ketika ada pembuktian. Maka,
atas fakta-fakta yang lemah dan janggal seperti ini, seharusnya hakim Tipikor Jakarta
Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Terdakwa menerima
eksepsi Terdakwa dan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima
surat dakwaan tersebut dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi
hukum. Karena dakwaan yang kabur (obscuur libel) sebagaimana termaktub dalam
Pasal 143 Ayat (3) KUHAP.
Ini selaras dengan azas van rechtswege nieting null and void
(suatu proses peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi
hukum) dan asas actore non probate, reus absolvitur (jika tidak dapat
dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan). Singkatnya, penuntut umum tidak dapat
membuktikan kesalahan terdakwa (actore non probate), terdakwa harus diputus
bebas (reus absolvitur).
Juga tidak ada aspek keadilan dan kemanfaatan dari proses
hukum Terdakwa bagi masyarakat, hingga hakim harus mempertimbangan ini secara
baik demi telaksananya due procces of law (proses hukum yang benar) dan
dihormatinya hak asasi Terdakwa. Mengacu pada prinsip kebebasan atau
indepedensi hakim yang yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di
Indinesia, hakim harus menerapkan hukum yang bersumber pada peraturan
perundang-undangan secara tepat, menafsirkan hukum dengan benar, sebagai wujud
kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (recht vinding). Hakim harus
membuktikan kepada publik bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
sangat dekat dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Hal tersebut merupakan kewenagan hakim dalam melakukan
konstruksi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun
2009 mengatakan, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Karena tujuan tertinggi hukum adalah melaksanakan keadilan. Mengutip Immanuel
Kant, filsuf Jerman sekitar 200 tahun lalu mengatakan, “…summum ius summa
injuria, summa lex summa crux” (kepastian hukum yang tertinggi adalah
ketidakadilan yang terbesar), karena itu, menunda-nunda keadilan (atau keadilan
yang datang terlambat) sama dengan tidak ada keadilan atau menolak keadilan itu
sendiri (justice delayed is justice denied), demikian kata William Glastone
(1809-1898), mantan Perdana Menteri Britania Raya. Kasus Bas dinilai penuh
dengan kejanggalan, karena kaburnya surat dakwaan dan terjadi kegamangan atau
skeptisisme dari hakim dalam memutus perkara tersebut, hingga dapat merugikan
hak konstitusional dan hak asasi Terdakwa sebagai warga negara yang wajib
diproteksi, dihormati, dan dipenuhi oleh siapa pun, termasuk penegak hukum
maupun negara sebagai wujud perlakuan yang sama di depan hukum (the equlity
before the law).
Hak-hak Terdakwa sudah dijamin oleh berbagai intrumen hukum
internasional maupun hukum positif, seperti Deklarasi Universal HAM PBB 10
Desember 948, Pasal 10 mengatakan, “Setiap orang, dalam persamaan yang penuh,
berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan
tidak memihak, dalam menetapakan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam
setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya”. Juga dalam Pasal 3 ayat (2)
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatakan, “Setiap orag berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat
kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Hak azasi manusia menurut pamfleter dan
intelektual Britania Raya, Thomas Paine, adalah jalan keluar untuk mengatasi
kesewenang-wenangan atau keadaan yang oleh aforisme Thomas Hobbes, homo homini
lupus est, bellum omnium contra omnes, manusia yang satu jadi serigala bagi
manusia lain, perang semua melawan semua. Maka seharusnya Terdakwa dibebaskan
demi hukum seperti ditegaskan dalam asas in dubio pro reo/exceptio format
regulam (jika ada keragu-raguan mengenai suatu hal, hakim harus menjatuhkan
hukuman yang meringankan terdakwa). Hakim adalah hukum yang berbicara (judex
set lex laguens).
Namun, putusan hakim pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap kasus korupsi mantan Gubernur Papua sekaligus mantan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Meksiko, Honduras, dan Panama ini tidak objektif dan mencederai rasa keadilan Terdakwa. Hingga memunculkan banyak pertanyaan: mengapa Bas dihukum, apa tujuannya, dan atas perintah siapa sampai digelar peradilan sesat atau miscarriage of justice terhadap Bas? Tindakan kriminalisasi ini perlu dijawab oleh negara (presiden) melalui rekomendasi (petunjuk) Mahkamah Agung (MA) untuk proses rehabilitasi nama baik dan martabat tokoh Papua Barnabas Suebu dan keluarga. Sebab destruksi penegakan hukum dan ketidakadilan pengadilan kasus Bas menjadi salah satu potret buruk dari sekian banyak ketidakadilan pengadilan terhadap orang asli Papua selama negeri ini diintegrasikan dengan Indonesia sejak 1 Mei 1963. Ini akan mempertebal ketidakpercayaan (distrust) warga Papua terhadap Jakarta dan terus mempertajam kecurigaan, dendaman, dan konfrontrasi tanpa akhir antara orang Papua dan pemerintah Indonesia. “Tidak ada batasan waktu untuk mencari kebenaran, karena kebenaran itu abadi dan tetap ada untuk menunggu mereka yang mencarinya!” Liberte.
Oleh: Thomas Ch Syufi
Penulis adalah Advokat muda Papua dan Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR)
Editor: Sianturi